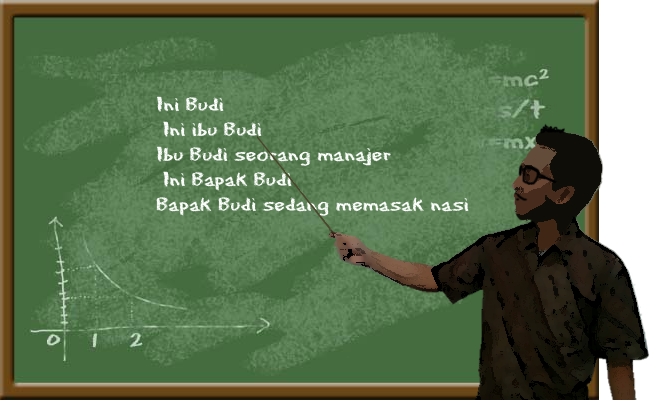Di sekolah manapun,
keterlambatan datang ke sekolah merupakan pelanggaran tata tertib. Yang
membedakan, tiap sekolah punya sanksi atau pun toleransi tertentu terhadap
siswa yang melakukannya. Demikian halnya yang berlaku di sekolah tempat saya
pernah mengajar.
Biasanya sekolah hanya
memberi toleransi 5 menit keterlambatan untuk dapat masuk kelas tanpa sanksi.
Kalau ada konsekuensi yang diterima paling-paling hanya beberapa menit
ketinggalan pelajaran. Tetapi, bagi beberapa siswa tampaknya konsekuensi itu
tidak seberapa merugikan. Kalau toh ada yang lebih merugikan paling-paling
perihal berkurangnya air di botol minum yang habis sebagian ditenggak setelah
harus lari kencang dari halte bus depan sekolah. Tetapi lain soal bagi mereka
yang finis di menit keenam. Guru piket pasti akan menanti di depan ruangan
kecil di pojok dekat tangga sebelah timur.
Secara administratif,
ada tiga tahap yang harus dilakukan guru piket pada saat itu. Yang pertama
adalah mendata nama-nama siswa beserta asal kelas mereka. Pada tahap ini proses
pedataan akan sangat merepotkan karena pendataan dilakukan orang per orang
secara manual, tidak secara kolektif. Penyebabnya karena setiap anak memiliki
akumulasi keterlambatan yang berbeda-beda. Akumulasi itulah yang dijadikan
pedoman dalam pemberian sanksi. Akumulasi keterlambatan sebanyak 5 kali akan mendapat surat peringatan pertama atau SP I
yang akan dikirimkan langsung kepada orang tua dari siswa yang bersangkutan.
Bagi siswa yang berlatar keluarga disiplin tinggi dan menjunjung tinggi
nilai-nilai peradaban moral yang baik, SP I adalah sebuah aib bagi orang
tuanya. SP I bisa menjadi bencana sesaat bagi siswa karena dengan sepucuk surat
itulah lazimnya ia akan melewati masa-masa tidak mengenakan seperti aneka
teguran, omelan, atau sanksi-sanksi
lain seperti larangan tidur malam atau larangan bermain video game yang diberlakukan leh orang tua mereka. Hal itu biasanya
cukup baik memberikan efek jera bagi siswa. Namun, efek jera itu tidak selalu
muncul pasca SP I. Rama contohnya. Siswa kelas IX tersebut pada hari itu baru
saja menggenapi akumulasi keterlambatannya menjadi 6 kali, yang artinya menurut aturan yang berlaku, ia harus
dipulangkan. Dan inilah reaksi Rama kepada saya ketika vonis pulang itu
dijatuhkan kepadanya:
“Ya sudah deh Pak, saya nelepon supir saya dulu ya. Sambil nunggu dijemput, saya boleh sarapan dulu ya Pak?”
Apakah Rama kapok?
Sepertinya tidak. Kepulangan siswa atas keterlambatan yang terakumulasi
sebanyak 6 kali berarti sebuah
“pemutihan”. Artinya, keterlambatan berikutnya (keenam) dihitung lagi sebagai
keterlambatan pertama pascavonis “pulang”. Dan dalam catatan keterlambatan yang
saya pegang ternyata Rama pernah 3 kali dipulangkan.
Tahap kedua dari proses
administrasi guru piket adalah meminta siswa untuk mengisi lembaran surat izin
masuk kelas dengan format isian berupa nama, kelas, dan tentunya alasan
keterlambatan. Bisa ditebak, untuk isian alasan keterlambatan jawaban paling
banyak adalah MACET. Ya iya lah... dari orok sampe nenek-nenek juga tau, mana ada Jakarta nggak macet *colek Bang Kumis.
Tahap ketiga, ini yang
paling memusingkan, yaitu pemberian sanksi. Inilah tahap ketika seorang guru
piket harus dituntut bersikap tegas dan hati-hati. Karena selain “SP“ dan
“dipulangkan”, tidak ada sanksi khusus terhadap keterlambatan mereka pada saat
itu. Semester lalu, keterlambatan paling
banyak terjadi di hari Kamis. Pada hari itu jam masuk sekolah lebih cepat 15
menit dari hari biasa untuk diisi dengan tadarus bagi yang muslim dan kegiatan
keagamaan lainnya bagi yang nonmuslim. Seperti biasa, memasuki menit keenam
berarti mereka yang terlambat harus lapor, kemudian mengisi format surat izin
masuk. Karena tidak adanya sanksi yang jelas, pada saat itu kami memberikan
ganjaran berupa setoran hapalan ayat surat-surat Juz ‘Ama. Maka inilah masalah
yang muncul:
Kami sebagai guru piket saat itu tidak memiliki data
tentang surat apa saja yang sudah dihapal oleh setiap siswa. Sehingga, ketika
diminta untuk menyetorkan hapalan ayat yang kami tentukan, mereka berdalih,
“Hapalan saya belum
sampai ke situ pak.”
“ Ya sudah surat apa
yang sudah kamu hapal?” tanya saya.
Dan ternyata saya sadar
bahwa pertanyaan itu sangatlah bodoh karena dengan sumringahnya siswa itu
menjawab,
“Surat Al-Insyiroh Pak,” sebuah surat pendek yang pastinya sangat mudah dihapal oleh
kebanyakan siswa.
Jelaslah bagi mereka itu
tidak seperti hukuman, melainkan hanya layaknya mengucapkan password dalam telekuis di radio untuk
maju ke tahap berikutnya. Tetapi
yang lebih bodoh dan konyol lagi jika situasi yang terjadi justru sebaliknya,
seperti berikut ini:
“Sudah sampai di mana hapalan kamu?” tanya saya.
“Surat
An-Nazi’at Pak,” jawab Bima,
dengan bangga. Pantas sejak tadi siswa itu tampak percaya diri walaupun datang
terlambat. Pastinya ia merasa lebih aman karena kemampuan hapalannya telah
melampaui teman-temannya. Setidaknya ia hanya butuh menghapal satu surat lagi
untuk bisa mendapatkan predikat tahfidz
juz ke-30. Predikat ini memang wajib disandang oleh seluruh siswa muslim karena
merupakan bagian dari profil lulusan sekolah ini .
“Baik, silakan!,” perintah saya dengan tegas
kepada Bima untuk memulai melantunkan hapalan suratnya itu. Namun tak ada yang
tahu bahwa di balik ucapan tegas itu tersipan rasa malu yang sedemikian besar
dan tak terkira. Terucaplah sebaris doa:
“Ya Allah Yang Mahakuasa. Demi
segala kuasamu mengendalikan apa yang ada dalam pikiran setiap manusia.
Janganlah sedikitpun Engkau alihkan pikiran dan konsentrasi Bima, muridku yang
baik nan soleh ini, selagi ia melantunkan ayat-ayatMu Ya Allah. Jagalah
kekhusyuannya dari segala gangguan yang ditimbulkan oleh jin dan syaitan serta
aneka mahluk ciptaanMu. Amiin ya robbal alamiiin.”
Ayat demi ayat yang dilantunkan Bima makin
membuat saya gemetar. Namun bukan sebab saya memahami makna yang
terlontar. Maka dalam hati terucaplah
kalimat istigfar,
“Astaghfirullaah al aziiim.”
Tuhan sesunguhnya tidak akan memberikan
cobaan di luar batas kesanggupan umatNya. Saya yakini itu betul-betul. Karena
itulah sebabnya Tuhan tidak membuat Bima lupa atau salah melafalkan
ayat-ayat-Nya. Betapa Tuhan tahu betul saya tidak akan sanggup memandu atau
mengoreksi satu ayat, bahkan sepenggal kata pun jika itu terjadi.
Masalah lain, sanksi menghapal ayat Juz
‘Ama benar-benar cukup menyita waktu dan
konsentrasi karena batas hapalan surat pada setiap siswa berbeda-beda, sehingga harus
dilakukan secara perorangan.
Sementara, sanksi ini jelas tidak bisa berlaku bagi siswa yang nonmuslim. Sehingga, dalam hal ini mereka sering terabaikan. Solusinya,
mereka harus duduk sendiri mempelajari kitab sucinya masing-masing.
Sampai pada suatu
ketika, tanpa sebab yang jelas masa berlaku sanksi berupa setoran hapalan ayat
ini habis begitu saja. Hampir dua minggu berlalu, nyaris tak ada lagi lantunan
ayat-ayat Juz ‘Ama dari mulut siswa yang terlambat. Entahlah, saya sendiri juga
tidak paham mengapa itu terjadi. Barangkali perangkat lunak sistem aturan main
sekolah mengenai sanksi keterlambatan sudah secara otomatis menghapus jenis
sanksi itu dari data base-nya karena
dianggap tidak efektif atau bahkan tidak relevan dengan tujuan yang diinginkan
: membuat siswa disiplin.
Pada masa kekosongan itu
saya sesekali memberlakukan sanksi klasik yang lazim diterapkan pada masa saya
sekolah dulu: lari keliling lapangan. Tetapi secara ekstrim saya lantas
teringat dengan kasus kekerasan mahasiswa STPDN, sebuah kasus yang membuat masyarakat makin
sangat gencar menuntut dihapuskannya sistem pemberian sanksi berupa fisik
terhadap anak didik. Dan sanksi itu pun akhirnya tidak saya lakukan lagi. Ini
bukan soal takut dikritik orang tua siswa, melainkan lebih tepatnya adalah
tidak mau mengambil risiko atas hal-hal buruk yang terjadi pada siswa. Padahal
saya paham betul, tidak semua sanksi fisik itu buruk dan tidak semua sanksi
nonfisik dapat membuat anak bertambah baik. Barangkali itulah salah satu yang
menyebabkan mental anak-anak jaman sekarang lebih lembek daripada anak-anak
yang hidup di masa lalu.
Jenis sanksi keterlambatan
pada akhirnya berujung pada sebuah perlakuan yang cukup efektif. Adalah sang
Kepsek, yang pada suatu ketika turun tangan mengambil alih tugas kami sebagai
guru piket. Dengan suara yang cukup lantang, beliau mengumpulkan anak-anak ke
tengah lapangan. Ternyata mereka diminta untuk mengumpulkan sampah yang
terlihat masih berserakan di lingkungan sekolah. Sebuah aktivitas yang sangat
meringankan beban sang Pramubhakti sekolah. Meski pagi itu sekolah sudah tampak
bersih dari sampah, anehnya siswa-siswa itu
tetap bisa menggengam sejumlah sampah di tangannya. Entah, apakah memang kerja
pramubhakti yang belum bersih benar, atau mungkin siswa-siswa yang sudah makin
kreatif. Karena, di pojok koridor timur terlihat Dika siswa kelas VII mengoyak
kertas dari buku tulisnya dan menggumpalkannya menjadi sebuah sampah yang
seakan-akan baru ia pungut dari tanah.